 |
| DOKTRIN & PRINSIP AHLUSSUNAH WAL JAMA’AH (Materi Sekolah Aswaja) |
Islam, iman dan ihsan adalah trilogi agama (addîn) yang membentuk tiga dimensi keagamaan meliputi syarî’ah sebagai realitas hukum, tharîqah sebagai jembatan menuju haqîqah yang merupakan puncak kebenaran esensial. Ketiganya adalah sisi tak terpisahkan dari keutuhan risalah yang dibawa Rasulullah saw. yang menghadirkan kesatuan aspek eksoterisme (lahir) dan esoterisme (batin). Tiga dimensi agama ini (Islam, iman dan ihsan), masing-masing saling melengkapi satu sama lain. KeIslaman seseorang tidak akan sempurna tanpa mengintegrasikan keimanan dan keihsanan. Ketiganya harus berjalan seimbang dalam perilaku dan penghayatan keagamaan umat, seperti yang ditegaskan dalam firman Allah: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. (QS. Albaqarah: 208). Imam Izzuddin bin Abdissalam mengatakan, “hakikat Islam adalah aktifitas badaniah (lahir) dalam menjalankan kewajiban agama, hakikat iman adalah aktifitas hati dalam kepasrahan, dan hakikat ihsan adalah aktifitas ruh dalam penyaksian (musyâhadah) kepada Allah”.
Dalam perkembangan selanjutnya, kecenderungan ulama dalam menekuni dimensi keIslaman, melahirkan disiplin ilmu yang disebut fiqh.Kecenderungan ulama dalam menekuni dimensi keimanan, melahirkan disiplin ilmu tauhid. Dan kecenderungan ulama dalam dimensi keihsanan, melahirkan disiplin ilmu tasawuf atau akhlak. Paham ASWAJA mengakomodir secara integral tiga dimensi keagamaan tersebut sebagai doktrin dan ajaran esensialnya. Karena praktek eksoterisme keagamaan tanpa disertai esoterisme, merupakan kemunafikan.Begitu juga esoterisme tanpa didukung eksoterisme adalah klenik. Semata-mata formalitas adalah tiada guna, demikian juga spiritualitas belaka adalah sia-sia. Imam Malik mengatakan: Barang siapa menjalani tasawuf tanpa fiqh, maka dia telah zindiq, barang siapa memegang fiqh tanpa tasawuf, maka dia telah fasiq, dan barang siapa menyatukan keduanya, maka dia telah menemukan kebenaran.
1. Doktrin Keimanan
Iman adalah pembenaran (tashdîq) terhadap Allah, Rasul dan segala risalah yang dibawanya dari Allah. Dalam doktrin keimanan, yang selanjutnya termanifestasi ke dalam bidang tauhid (teologi/kalam) ini, ASWAJA berpedoman pada akidah Islamiyah (ushûluddîn) yang dirumuskan oleh Abu Alhasan Al’asy’ari (260 H./874 M. – 324 H./936 M.) dan Abu Manshur Almaturidi (w. 333 H.). Kedua tokoh ASWAJA ini nyaris sepakat dalam masalah akidah Islamiyah, meliputi sifat-sifat wajib, mustahil dan ja’iz bagi Allah, para rasul dan malaikatNya, kendati keduanya berbeda dalam cara dan proses penalaran. Kedua tokoh ini hanya berbeda dalam tiga masalah yang tidak berakibat fatal. Yaitu dalam masalah istitsnâ’, takwîn, dan iman dengan taqlid.
Pertama istitsna’, atau mengatakan keimanan dengan insya’Allah, seperti “Penulis beriman, insya’Allah”, menurut Maturidiyah tidak diperbolehkan, karena istitsnâ demikian mengisyaratkan sebuah keraguan, dan keimanan batal dengan adanya ragu-ragu. Menurut Asyâ’irah diperbolehkan, karena maksud istisnâ’ demikian bukan didasari keraguan atas keimanan itu sendiri, melainkan keraguan tentang akhir hidupnya dengan iman atau tidak, na’ûdzu billahmin dzalik. Atau, istitsnâ’ demikian maksudnya keraguan dan spekulasi terhadap kesempurnaan imannya di hadapan Allah. Kedua sifat takwîn (mewujudkan), menurut Asyâ’irah sifat takwîn (تكوین) tidak berbeda dengan sifat Qudrah. Sedangkan menurut Maturidiyah, takwîn adalah sifat tersendiri yang berkaitan dengan sifat Qudrah. Dan ketiga, tentang imannya orang yang taqlid
(ikut-ikutan tanpa mengetahui dalilnya). Menurut Maturidi, imannya muqallid sah dan disebut arif serta masuk surga. Sedangkan Menurut Abu Alhasan Al’asy’ari, keimanan demikian tidak cukup. Sedangkan Asyâ’irah (pengikut Abu Alhasan Al’asy’ari) berbeda pendapat tentang imannya muqallid. Sebagian menyatakan mukmin tapi berdosa karena tidak mau berusaha mengetahu melalui dalil; sebagian mengatakan mukmin dan tidak berdosa kecuali jika mampu mengetahui dalil; dan sebagian yang lain mengatakan tidak dianggap mukmin sama sekali. Dari tingkatan tauhid ini, selanjutnya ada empat strata keimanan. Ada iman bittaqlîd, iman biddalîl, iman bil iyyân dan iman bil haqq. Pertama, iman bittaqlîd adalah keimanan melalui ungkapan orang lain tanpa mengetahui dalilnya secara langsung. Keimanan seperti ini keabsahannya masih diperselisihkan. Kedua, iman biddalîl (ilmul yaqîn) ialah keyakinan terhadap aqâ’id lima puluh dengan dalil dan alasan filosofinya. Dua strata keimanan ini masih terhalang (محجوب) dalam mengetahui Allah. Ketiga, iman bil iyyân (‘ainul yaqîn) ialah keimanan yang senantiasa hatinya muraqabah kepada Allah. Artinya, dalam kondisi apapun, Allah tidak hilang dari kesadaran hatinya. Dan keempat, iman bil haqq (haqqul yaqîn) yaitu keimanan yang telah terlepas dari segala yang hadîts dan tenggelam dalam fanâ’ billah. Mempelajari ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf, hanya akan menghasilkan iman biddalîl (ilmul yaqîn), dan jika keimanan ini senantiasa disertai kesadaran hati dan penghayatan amaliah, maka naik ke strata iman biliyyân (‘ainul yaqîn) hingga puncaknya mencapai pada iman bil haqq (haqqul yaqîn).
Doktrin keimanan terhadap Allah, berarti tauhid atau meng-Esakan Allah dalam af’âl, shifah dan dzât. Dengan demikian, tauhid terbagi menjadi tiga: Tauhid fi’li, yaitu fana’ dari seluruh perbuatan; tauhid washfi, yaitu fana’ dari segala sifat; dan tauhiddzati, yaitu fana’ dari segala yang maujûd. Fana’ fi’li disebut juga dengan ilmul yaqîn, fana’ washfi disebut juga dengan ‘ainul yaqîn, dan fana’ dzati juga disebut dengan haqqul yaqîn. Level tauhid demikian ini merupakan puncak prestasi dari penghayatan firman Allah: Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu.(QS. Ashshafat: 96). Sebagian ulama ‘arif billah menyatakan: Barang siapa dapat menyaksikan makhluk tidak memiliki perbuatan, maka ia telah beruntung, barang siapa menyaksikannya tidak hidup, maka itu diperbolehkan, dan barang siapa menyaksikannya praktis tiada, maka ia telah wushul. Konsep tauhid ASWAJA mengenai af’âl (perbuatan) Allah, berada di tengah antara paham Jabariyah di satu pihak dan Qadariyah dan Mu’tazilah di pihak lain. Ketika Jabariyah menyatakan paham peniadaan kebebasan dan kuasa manusia atas segala kehendak dan perbuatannya secara mutlak, sementara Qadariyah dan Mu’tazilah menyatakan makhluk memiliki kebebasan dan kuasa mutlak atas kehendak dan perbuatannya, maka lahirlah ASWAJA sebagai sekte moderat di antara dua paham ektrim tersebut. ASWAJA meyakini bahwa makhluk memiliki kebebasan kehendak (ikhtiyar) namun tidak memiliki kuasa (qudrah) perbuatan selain sebatas kasb (upaya). Dalam keyakinan ASWAJA, secara dhahir manusia adalah ‘kuasa’ (memiliki qudrah), namun secara batin, manusia adalah majbûr (tidak memiliki qudrah apapun).
Dalam doktrin keimanan ASWAJA, keimanan seseorang tidak dianggap hilang dan menjadi kafir, dengan melakukan kemaksiatan. Seseorang yang melakukan maksiat ataupun bid’ah, sementara hatinya masih teguh meyakini dua kalimat syahadat, maka ASWAJA tidak akan menvonis sebagai kafir, melainkan sebagai orang yang sesat (dhalâl) dan durhaka. ASWAJA sangat berhati-hati dan tidak gampang dalam sikap takfîr (mengkafirkan). Karena memvonis kafir seseorang yang sejatinya mukmin akan menjadi bumerang bagi diri sendiri. Rasulullah saw. bersabda: Ketika seseorang berkata kepada saudaranya: “wahai seorang yang kafir”, maka salah satunya benar-benar telah kafir. (HR. Bukhari)
Keimanan seseorang akan hilang dan menjadi kafir (murtad) apabila menafikan wujud Allah, mengandung unsur syirik yang tidak dapat dita’wil, mengingkari kenabian, mengingkari hal-hal yang lumrah diketahui dalam agama (ma’lûm bi adldlarûri), dan mengingkari hal-hal mutawâtir atau mujma’ ‘alaih yang telah lumrah diketahui. Tindakan yang menyebabkan seseorang dikategorikan kafir bisa meliputi ucapan, perbuatan atau keyakinan, yang mengandung unsur-unsur di atas ketika telah terbukti (tahaqquq) dan tidak bisa dita’wil.
2. Doktrin KeIslaman
Doktrin keIslaman, yang selanjutnya termanifestasi ke dalam bidang fiqh yang meliputi hukum-hukum legal-formal (ubudiyah, mu’amalah, munakahah, jinayah, siyasah dan lain lain), ASWAJA berpedoman pada salah satu dari empat madzhab fiqh: Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah. Ada alasan mendasar mengenai pembatasan ASWAJA hanya kepada empat madzhab ini. Di samping alasan otentisitas madzhab yang terpercaya melalui konsep-konsep madzhab yang terkodifikasi secara rapi dan sistematis, metodologi pola pikir dari empat madzhab ini relatif tawâzun (berimbang) dalam mensinergikan antara dalil aql (rasio-logis) dan dalil naql (teks-teks keagamaan). Empat madzhab ini yang dinilai paling moderat dibanding madzhab Dawud Adhdhahiri yang cenderung tekstualis dan Madzhab Mu’tazilah yang cenderung rasionalis. Jalan tengah (tawâsuth) yang ditempuh ASWAJA di antara dua kutub ekstrim, yaitu antara rasioalis dengan tekstualis ini, karena jalan tengah atau moderat diyakini sebagai jalan paling selamat di antara yang selamat, jalan terbaik diantara yang baik, sebagaimana yang ditegaskan Nabi saw. dalam sabdanya: Sebaik-baiknya perkara adalah tengahnya.
Dengan prinsip inilah ASWAJA mengakui bahwa empat madzhab yang memadukan dalil Alqur’an, Hadits, Ijma’ dan Qiyas (analogi), diakuinya mengandung kemungkinan lebih besar berada di jalur kebenaran dan keselamatan. Hal ini juga dapat berarti bahwa kebenaran yang diikuti dan diyakini oleh ASWAJA hanya bersifat kemungkinan dan bukan kemutlakan. Dalam arti, mungkin benar dan bukan mutlak benar. Empat dalil (Alqur’an, Hadits, Ijma’ dan Qiyas) ini dirumuskan dari ayat: Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya) (QS. Annisa’: 59)
Dalam ayat ini secara implisit ditegaskan, bahwa ada empat dalil yang bisa dijadikan tendensi penggalian (istinbâth) hukum, yaitu Alqur’an, Hadits, Ijma’ dan Qiyas. Perintah taat kepada Allah dan utusanNya, berarti perintah berpegang pada Alqur’an dan Hadits, perintah taat kepada ulil amri berarti perintah berpegang pada Ijma’ (konsensus) umat (mujtahidîn), dan perintah mengembalikan perselisihan kepada Allah dan RasulNya berarti perintah berpegang pada Qiyas sepanjang tidak ada nash dan ijma’. Sebab, Qiyas hakikatnya mengembalikan sesuatu yang berbeda pada hukum Allah dan utusanNya.
Disamping itu, ASWAJA juga melegalkan taqlid, bahkan mewajibkannya bagi umat yang tidak memiliki kapasitas dan kualifikasi keilmuan yang memungkinkan melakukan ijtihad. Taqlid hanya haram bagi umat yang benar-benar memiliki kapasitas dan piranti ijtihad sebagaimana yang dikaji dalam kitab Ushul Fiqh. Dengan demikian, ASWAJA tidak pernah menyatakan pintu ijtihad tertutup. Pintu ijtihad selamanya terbuka, hanya saja umat Islam yang agaknya dewasa ini ‘enggan’ memasukinya. Mewajibkan ijtihad kepada umat yang tidak memiliki kapasitas ijtihad, sama saja memaksakan susuatu di luar batas kemampuannya. Maka kepada umat seperti inilah taqlid dipahami sebagai kewajiban oleh ASWAJA berdasarkan firman Allah: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (QS. Annahl: 43)
3. Doktrin Keihsanan
Tasawuf adalah sebuah manhaj spiritual yang bisa dilewati bukan melalui teori-teori ilmiah semata melainkan dengan mengintegrasikan antara ilmu dan amal, dengan jalan melepaskan (takhallî) baju kenistaan (akhlaq madzmûmah) dan mengenakan (tahallî) jubah keagungan (akhlaq mahmûdah), sehingga Allah hadir (tajallî) dalam setiap gerak-gerik dan perilakunya, dan inilah manifestasi konkret dari ihsan dalam sabda Rasulullah SAW: Ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah engkau melihatNya, dan jika engkau tidak melihatNya, sesungguhnya Dia melihatmu.
Doktrin keihsanan, yang selanjutnya termanifestasi ke dalam bidang tasawuf atau akhlaq
ini, ASWAJA berpedoman pada konsep tasawuf akhlaqi atau amali, yang dirumuskan oleh Imam Aljunaid Albaghdadi dan Alghazali. Limitasi (pembatasan) hanya kepada kedua tokoh ini, tidak berarti manafikan tokoh-tokoh tasawuf falsafi dari kelompok ASWAJA, seperti Ibn Al’arabi, Alhallaj dan tokoh-tokoh sufi ‘kontroversial’ lainnya. Dari uraian di atas, dapat dimengerti bahwa kelompok yang masuk kategori ASWAJA meliputi ahli tauhid (kalam), ahli fiqh (syariat), ahli tasawuf (akhlak) dan bahkan ahli hadits (muhadditsîn). Dari kelompok-kelompok ini masing-masing memiliki konsep metodologis dan tema kajian sendiri-sendiri yang tidak bisa diuraikan di makalah ringkas ini.
B. Metodologi Pemikiran (Manhajul fikr) Aswaja
Jika kita mencermati doktrin-doktrin paham ASWAJA, baik dalam akidah (iman), syariat (Islam) ataupun akhlak (ihsan), maka bisa kita dapati sebuah metodologi pemikiran (manhaj alfkr) yang tengah dan moderat (tawassuth), berimbang atau harmoni (tawâzun), netral atau adil (ta’âdul), dan toleran (tasâmuh). Metodologi pemikiran ASWAJA senantiasa menghidari sikap-sikap tatharruf (ekstrim), baik ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Inilah yang menjadi esensi identitas untuk mencirikan paham ASWAJA dengan sekte-sekte Islam lainnya. Dan dari prinsip metodologi pemikiran seperti inilah ASWAJA membangun keimanan, pemikiran, sikap, perilaku dan gerakan.
1. Tawasuth (Moderat)
Tawassuth ialah sebuah sikap tengah atau moderat yang tidak cenderung ke kanan atau ke kiri. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, pemikiran moderat ini sangat urgen menjadi
semangat dalam mengakomodir beragam kepentingan dan perselisihan, lalu berikhtiar mencari solusi yang paling ashlah (terbaik). Sikap ini didasarkan pada firman Allah: Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. (QS. Albaqarah: 143).
2. Tawâzun (Berimbang)
Tawâzun ialah sikap berimbang dan harmonis dalam mengintegrasikan dan mensinergikan dalil-dalil (pijakan hukum) atau pertimbangan-pertimbangan untuk mencetuskan sebuah keputusan dan kebijakan.Dalam konteks pemikiran dan amaliah keagamaan, prinsip tawâzun menghindari sikap ekstrim (tatharruf) yang serba kanan sehingga melahirkan fundamentalisme, dan menghindari sikap ekstrim yang serba kiri yang melahirkan liberalisme dalam pengamalan ajaran agama. Sikap tawâzun ini didasarkan pada firman Allah: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. (QS. Alhadid: 25).
3. Ta’âdul (Netral dan Adil)
Ta’âdul ialah sikap adil dan netral dalam melihat, menimbang, menyikapi dan menyelesaikan segala permasalahan. Adil tidak selamanya berarti sama atau setara (tamâtsul). Adil adalah sikap proporsional berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing. Kalaupun keadilan menuntut adanya kesamaan atau kesetaraan, hal itu hanya berlaku ketika realitas individu benarbenar sama dan setara secara persis dalam segala sifat-sifatnya. Apabila dalam realitasnya terjadi tafâdlul (keunggulan), maka keadilan menuntut perbedaan dan pengutamaan (tafdlîl). Penyetaraan antara dua hal yang jelas tafâdlul, adalah tindakan aniaya yangbertentangan dengan asas keadilan itu sendiri. Sikap ta’âdul ini berdasarkan firman Allah: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. (QS. Alma’idah: 8).
4. Tasâmuh (toleran)
Tasâmuh ialah sikap toleran yang bersedia menghargai terhadap segala kenyataan
perbedaan dan keanekaragaman, baik dalam pemikiran, keyakinan, sosial kemasyarakatan, suku, bangsa, agama, tradisi-budaya dan lain sebagainya.Toleransi dalam konteks agama dan keyakinan bukan berarti kompromi akidah. Bukan berarti mengakui kebenaran keyakinan dan kepercayaan orang lain. Toleransi agama juga bukan berarti mengakui kesesatan dan kebatilan sebagai sesuatu yang haq dan benar.Yang salah dan sesat tetap harus diyakini sebagai kesalahan dan kesesatan. Dan yang haq dan benar harus tetap diyakini sebagai kebenaran yang haq. Dalam kaitannya dengan toleransi agama, Allah SWT berfirman: Untukmulah agamamu, dan untukkulah, agamaku. (QS. Alkafirun: 6). Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. (QS. Ali Imran: 85)
Toleransi dalam konteks tradisi-budaya bangsa, ialah sikap permisif yang bersedia menghargai tradisi dan budaya yang telah menjadi nilai normatif masyarakat. Dalam pandangan ASWAJA, tradisi-budaya yang secara substansial tidak bertentangan dengan syariat, maka Islam akan menerimanya bahkan mengakulturasikannya dengan nilai-nilai keIslaman.
Dengan demikian, tasâmuh (toleransi), berati sebuah sikap untuk menciptakan keharmonisan kehidupan sebagai sesama umat manusia. Sebuah sikap untuk membangun kerukunan antar sesama makhluk Allah di muka bumi, dan untuk menciptakan peradaban manusia yang madani. Dari sikap tasâmuh inilah selanjutnya ASWAJA merumuskan konsep persaudaraan (ukhuwwah) universal. Meliputi ukhuwwah Islamiyyah (persaudaan keIslaman), ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan kebangsaaan) dan ukhuwwah basyariyyah atau insâniyyah (persaudaraan kemanusiaan). Persaudaraan universal untuk menciptakan keharmonisan kehidupan di muka bumi ini, merupakan implementasi dari firman Allah SWT: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. (QS. Alhujurat; 13). Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. (QS. Albaqarah: 30)
C. Esensi Khilafah dalam Pandangan Aswaja
Dalam pandangan ASWAJA, esensi dan hakikat dari sebuah pemerintahan atau negara (khilafah), adalah sebagai salah satu diantara instrumen (wasâ’il) untuk usaha terwujudnya aplikasi syariat secara totalitas (kâffah) dalam kehidupan umat melalui kewajiban menegakkan amar ma’ruf nahi munkar, yang menjadi cita-cita dan tujuan akhirnya (maqâshid). Karena kedudukannya yang dipandang sebagai wasîlah untuk maqâshid berupa tugas amar ma’ruf nahi munkar, maka pemerintahan atau negara tidak harus terikat dengan bentuk, sistem ataupun dasar idiologi negara tertentu. Apapun sistem, bentuk ataupun dasar idiologi yang diberlakukan, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan tidak menjadi rintangan dalam tugas dakwah Islamiyah, serta tidak menghalangi umat Islam dalam menjalankan praktek keagamaannya, maka tidak ada kewajiban untuk melakukan kudeta atau merubahnya. Merubah bentuk, sistem atau dasar idiologi negara, hanya wajib dilakukan-sesuai batas kemampuan-jika nyata-nyata bertentangan dengan syariat.
Pendirian Khilafah Islamiyah bagi ASWAJA (baca: Nahdlatul Ulama) dalam konteks keIndonesiaan, bukanlah cita-cita urgen, sebab eksistensinya hanyalah sebagai wasîlah. Ada citacita (maqâshid) yang jauh lebih penting dan esensial dari sekedar membentuk instrumen perjuangan, yaitu menegakkan amar ma’ruf nahi munkar di tengah kehidupan masyarakat, dan tugas maqâshid ini bisa dilangsungkan tidak harus melalui pendirian Khilafah Islamiyah.
Pandangan seperti inilah yang mendasari sikap ASWAJA (baca: NU) yang tidak ambisi dan bercita-cita mendirikan Khilafah Islamiyah di Indonesia. Karena khilafah bukanlah satusatunya instrumen yang bisa ditempuh untuk menegakkan syariat dalam kehidupan umat.Bahkan selama ini, setiap usaha merubah bentuk dan dasar hukum negara, nyata-nyata lebih banyak memunculkan ekses negatif yang justru merugikan kaum Muslimin sendiri.Gerak perjuangan ASWAJA (NU) dalam konteks Indonesia, bukan semangat perjuangan mendirikan Khilafah Islamiyah, melainkan semangat perjuangan menegakkan syariat dalam perilaku keseharian umat. Dengan kata lain, perjuangan ASWAJA (NU) tidak dikonsentrasikan pada pembentukan sebuah wadah syariat secara formal, berupa bentuk khilafah atau sistem negara Islam, melainkan lebih dikonsentrasikan pada perjuangan aplikasi syariat dalam perilaku umat sehingga menjadi ruh dan substansi perilaku kehidupan masyarakat. Perilaku umat yang berlandaskan syariat jauh lebih penting dan lebih baik dibanding sekedar formalitas bentuk dan sistem negara Islami.
Hal ini logis, sebab jika kita jujur membaca fakta sejarah khilafah dalam Islam, sebenarnya yang layak dilabeli dengan ‘Islamiyah’ (baca: demokratis), hanyalah khilafah era Khulafa’ Arrasyidin saja. Khilafah pasca Khulafa’ Arrasyidin, secara umum telah kehilangan label ke Islamiyah-annya, bahkan identik dengan sistem kekaisaran Romawi dan Persi.Dari sejarah ini pula bisa kita tegaskan bahwa sistem pemerintahan demokrasi sebenarnya tidak bisa diklaim sebagai produk kafir, sebab khilafah era Khulafa’ Arrasyidin adalah pemerintahan paling demokratis dari sistem demokrasi manapun.
Disamping itu, misi pendirian kembali Khilafah Islamiyah yang diusung oleh sebagian sekte dan gerakan Islam dalam konteks Indonesia dewasa ini, faktanya tidak murni hanya mengusung misi mendirikan negara Islam saja, melainkan juga mengusung paham dan idiologi aliran mereka, seperti idiologi Wahabi, Syi’ah atau lainnya. Mereka tidak akan mendirikan Khilafah Islamiyah kecuali paham dan idiologi mereka juga menjadi paham dan idiologi resmi pemerintah. Artinya, ketika khilafah berhasil didirikan, bukan mustahil mereka memberhangus kelompok ASWAJA yang bertentangan dengan paham mereka, seperti sejarah kekejaman Pemerintahan Arab Saudi dengan paham Wahhabinya.
Inilah yang menjadi alasan fundamental kenapa ASWAJA (NU) menentang setiap gerakan dan sekte yang mengusung Khilafah Islamiyah di Indonesia dan merongrong NKRI yang beridiolgi Pancasila. Dengan kenyakinan bahwa sila pertama yang mencerminkan tauhid Islam telah menjiwai sila-sila lain dalam Pancasila, dan mempertimbangkan kenyataan rakyat bangsa Indonesia yang plural dalam ras, suku dan agama, serta mempertimbangkan resiko ancaman integritas bangsa, maka ASWAJA (NU) menyatakan: bahwa NKRI dan Pancasila sebagai idiologinya, adalah final dari segala upaya membentuk negara di Indonesia. Sikap seperti ini bukan berarti ASWAJA (NU) anti khilafah, melainkan lebih demi mempertahankan eksistensi idiologi ASWAJA dan menghindarkan kekacauan umum (chaos) yang harus diprioritaskan dari sekedar mencapai kemaslahatan (mendirikan khilafah), sesuai kaidah fiqh:
Menghindari kekacauan lebih diprioritaskan dari mengupayakan kemaslahatan
Apabila sejauh ini dikenal tiga model hubungan agama-negara, yaitu hubungan intergasi (agama dan negara adalah satu kesatuan); hubungan sekuler (pemisahan peran agama dalam pemerintahan); dan hubungan simbiosis (agama-negara terpisah namun saling membutuhkan dan mengisi secara timbal-balik), maka model ketiga inilah yang menjadi pilihan ASWAJA dalam memandang hubungan agama dan negara.Agama tidak harus diformalkan sebagai sebuah sistem dan bentuk suatu negara, namun agama juga tidak boleh diceraikan dari intervensi peran politik.
Pandangan politik ASWAJA seperti ini, tidak bisa dipertentangkan dengan muatan surat Alma’idah ayat 44, 45 dan 47, yang memvonis kafir, dhalim dan fasiq bagi orang yang tidak memberlakukan hukum-hukum yang diturunkan Allah. Vonis kafir, dhalim dan fasiq dalam tiga ayat tersebut meski berlaku bagi umat Islam atau ahli alkitab (non Muslam), namun bila dilakukan orang mukmin, menurut Thawus: “kekafiran itu tidak mengeluarkannya dari agama”.Dan menurut Atha’; “kekafiran di bawah kekafiran, kedhaliman di bawah kedhaliman, dan kefasikan di bawah kefasikan”. Sedangkan dalam riwayat lain menurut Ibn Abbas, penguasa Muslim yang tidak memberlakukan hukum sesuai apa yang diturunkan Allah dipilah menjadi dua. Ibn Abbas mengatakan: “Orang yang mengingkari apa yang diturunkan Allah, maka dia adalah kafir, dan orang yang membenarkannya namun tidak menerapkannya, maka dia dhalim atau fasiq”. Dari sini bisa dipahami bahwa, apabila tidak memberlakukan hukum-hukum yang diturunkan Allah lantaran ketidaksanggupan, atau karena justeru akan menimbulkan bahaya dan kerusakan (mafâsid), seperti ancaman disintegrasi bangsa, tekanan internasional dll., maka vonis kafir, dhalim dan fasiq tidak bisa dijatuhkan kepada umat Islam.
Disusun Oleh: Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A.
Alumnus S1 Universitas Islam Negeri (Uin) Sunan Kalijaga Jogjakarta
Alumnus S2 Sosiologi Fisipol Universitas Gadjah Mada (Ugm) Jogjakarta
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Pmii) Daerah Istimewa Jogjakarta
Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghozali (Unugha) Cilacap
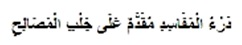










1 comment:
ayo segera bergabung dengan saya di D3W4PK
hanya dengan minimal deposit 10.000 kalian bisa menangkan uang jutaan rupiah
ditunggu apa lagi ayo segera bergabung, dan di coba keberuntungannya
untuk info lebih jelas silahkan di add Whatshapp : +8558778142
terimakasih ya waktunya ^.^
Post a Comment